PERANG yang Terjadi Tanpa Pengakuan: Realitas Proxy War. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia semakin dihadapkan pada konflik-konflik bersenjata yang melibatkan aktor-aktor negara namun diselimuti oleh lapisan ketidakjelasan. Di balik pertempuran yang terjadi di wilayah-wilayah seperti Yaman, Suriah, Ukraina Timur, dan Gaza, sering kali terdapat kepentingan kekuatan besar yang saling bertarung secara tidak langsung. Fenomena ini dikenal sebagai proxy war atau perang perwakilan — sebuah bentuk konflik modern yang terus berkembang, kompleks, dan sulit dikendalikan secara hukum.
Di Yaman, kelompok Houthi yang menyerang Israel diduga mendapat dukungan dari Iran, sementara Israel mendapatkan dukungan militer dari Amerika Serikat. Di Suriah, kelompok-kelompok bersenjata yang saling berlawanan juga dipersenjatai oleh kekuatan besar dengan tujuan geopolitik masing-masing. Bahkan konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina pun kerap digambarkan sebagai perpanjangan dari perseteruan strategis antara Rusia dan blok Barat, termasuk NATO dan Amerika Serikat.
Fenomena perang proxy seperti ini bukan hanya menyulitkan identifikasi tanggung jawab hukum, tetapi juga menantang keefektifan hukum internasional yang dirancang berdasarkan asumsi tradisional: bahwa perang terjadi secara langsung antara dua negara yang jelas identitas dan intensinya.
Pengertian dan Akar Historis Proxy War
Perang proxy (proxy war) adalah konflik bersenjata di mana dua atau lebih kekuatan besar berperang tidak secara langsung, tetapi melalui pihak ketiga — baik negara lain, kelompok pemberontak, milisi, atau organisasi non-negara. Dalam konteks ini, pihak-pihak utama menyediakan senjata, pelatihan, intelijen, atau dukungan diplomatik kepada aktor-aktor perwakilan mereka, namun tidak terlibat langsung sebagai pelaku tempur.
Sejarah perang proxy sangat lekat dengan dinamika Perang Dingin. Saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan superpower menghindari konfrontasi langsung karena risiko nuklir yang tinggi. Sebagai gantinya, mereka mendukung pihak-pihak tertentu dalam konflik regional di berbagai belahan dunia, seperti di Korea, Vietnam, Afganistan, Angola, dan Amerika Latin.
Di balik strategi ini, tersembunyi logika geopolitik: dengan memanfaatkan pihak ketiga, negara besar dapat memperluas pengaruhnya, menghambat musuhnya, tanpa menanggung konsekuensi politik, ekonomi, dan militer dari keterlibatan langsung. Namun, strategi ini juga menyuburkan perang berkepanjangan, kehancuran infrastruktur, krisis kemanusiaan, serta sulitnya penyelesaian konflik secara damai.
Beberapa Contoh Nyata Proxy War Perang Korea (1950–1953)
Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan sebenarnya adalah bagian dari tarik-menarik antara dua blok kekuatan: Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sementara Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu Barat. Walaupun konflik telah berhenti secara aktif sejak 1953 melalui armistice, namun secara hukum, kedua negara belum menandatangani perjanjian damai.
Perang Vietnam (1955–1975)
Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan dalam menghadapi Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Ini adalah salah satu contoh perang proxy yang paling destruktif, dengan jutaan korban jiwa dan dampak psikologis, ekonomi, serta lingkungan yang berkepanjangan.
Perang Afghanistan (1979–1989)
Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan, Amerika Serikat mendukung kelompok mujahidin (termasuk yang kelak menjadi cikal bakal Taliban dan Al-Qaeda) dengan persenjataan dan pelatihan. Tujuannya adalah melemahkan pengaruh Soviet di Asia Tengah. Perang ini menjadi pelajaran kelam tentang bagaimana perang proxy dapat menciptakan “monster” baru di masa depan.
Perang Yaman dan Serangan Houthi ke Israel (2015–sekarang)
Konflik ini melibatkan Arab Saudi dan Iran, serta diperluas dengan keterlibatan AS dan Israel. Dukungan Iran terhadap Houthi di satu sisi, dan aliansi militer AS-Israel di sisi lain, memperlihatkan dimensi perang proxy di Timur Tengah yang makin kompleks.
Regulasi Hukum Internasional dan Tantangannya
Dalam teori, hukum internasional memberikan kerangka normatif yang jelas terkait penggunaan kekerasan melalui Piagam PBB, konvensi-konvensi hukum humaniter (Geneva Conventions), dan prinsip non-intervensi. Namun, perang proxy kerap kali memanfaatkan celah hukum yang ada:
Pasal 2(4) Piagam PBB melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Namun, dalam perang proxy, aktor utama kerap mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan langsung, melainkan hanya memberi “dukungan teknis”.
Prinsip non-intervensi melarang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Namun, doktrin “dukungan terhadap pemberontakan yang sah” atau “perlindungan terhadap populasi sipil” kerap dijadikan dalih pembenaran.
Hukum humaniter internasional (IHL) memang mengatur konflik bersenjata non-internasional (NIAC), tetapi dalam kasus perang proxy, status hukum aktor sering diperdebatkan: apakah kelompok bersenjata tersebut merupakan pihak dalam NIAC, apakah memiliki hubungan yang cukup erat dengan negara pendukung, atau hanya sekadar “proxy”?
Tanggung jawab negara (State Responsibility) atas tindakan proxy masih menjadi medan perdebatan. Apakah negara pendukung bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter oleh kelompok yang didukungnya? ICJ dalam kasus Nicaragua v. United States (1986) menyatakan bahwa AS bertanggung jawab karena mengorganisir, melatih, dan mendanai kelompok Contras, namun standar “efektif control” ini kerap dianggap terlalu tinggi dan sulit dibuktikan.
Apakah Dibutuhkan Rezim Baru Hukum Internasional?
Dengan semakin berkembangnya pola perang proxy, muncul pertanyaan mendasar: Apakah hukum internasional saat ini cukup memadai untuk mengatur fenomena ini?
Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Di satu sisi, instrumen hukum yang ada sebenarnya sudah cukup komprehensif. Namun di sisi lain, realitas politik dan teknologi modern membuat instrumen itu sering kali tidak efektif. Masalah utama bukan hanya pada kekosongan hukum, tetapi lebih pada lemahnya penegakan hukum, bukti hubungan antara proxy dan negara pendukung, serta komitmen politik negara-negara besar.
Meski demikian, sejumlah kalangan mulai mendorong perumusan dokumen baru atau komentar umum oleh lembaga seperti Komite HAM PBB, Komite ICRC, atau bahkan melalui resolusi Majelis Umum PBB untuk memperjelas tanggung jawab negara dalam konteks perang proxy. Konsep seperti “indirect aggression”, “remote warfare accountability”, atau “transnational military assistance regulation” menjadi diskursus yang berkembang.
Alternatif lainnya adalah mendorong penguatan yurisprudensi melalui pengadilan internasional (ICJ, ICC), yang bisa memperjelas parameter hubungan antara aktor negara dan non-negara dalam konflik bersenjata.
Penutup
Perang proxy bukanlah fenomena baru, namun signifikansinya dalam dinamika konflik global saat ini semakin meningkat. Hukum internasional menghadapi tantangan serius dalam mengatur dan mengendalikan konflik model ini, terutama karena keterlibatan negara sering kali disamarkan. Oleh karena itu, selain pembaruan normatif, yang lebih penting adalah penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi, serta keberanian komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap negara-negara yang bermain di balik layar.
Selama negara-negara besar masih mempraktikkan politik kekuasaan melalui pihak ketiga, dan selama tidak ada konsensus global untuk membatasi bentuk-bentuk campur tangan tidak langsung, maka perang proxy akan tetap menjadi wajah gelap dari tatanan internasional. (***)





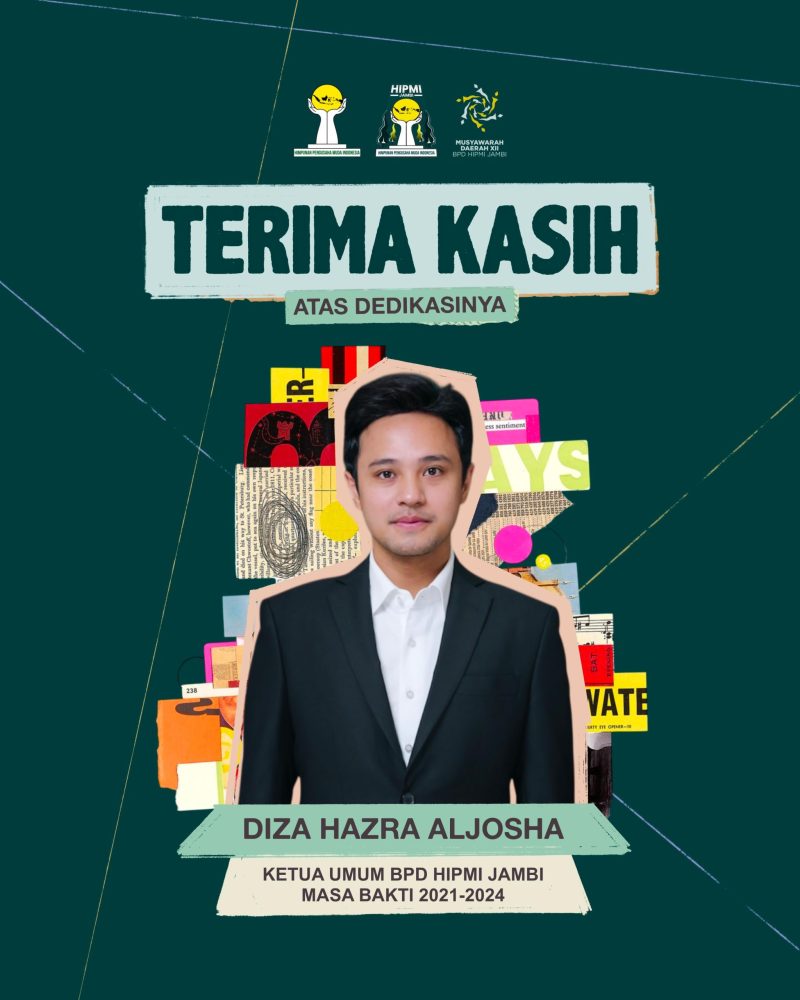
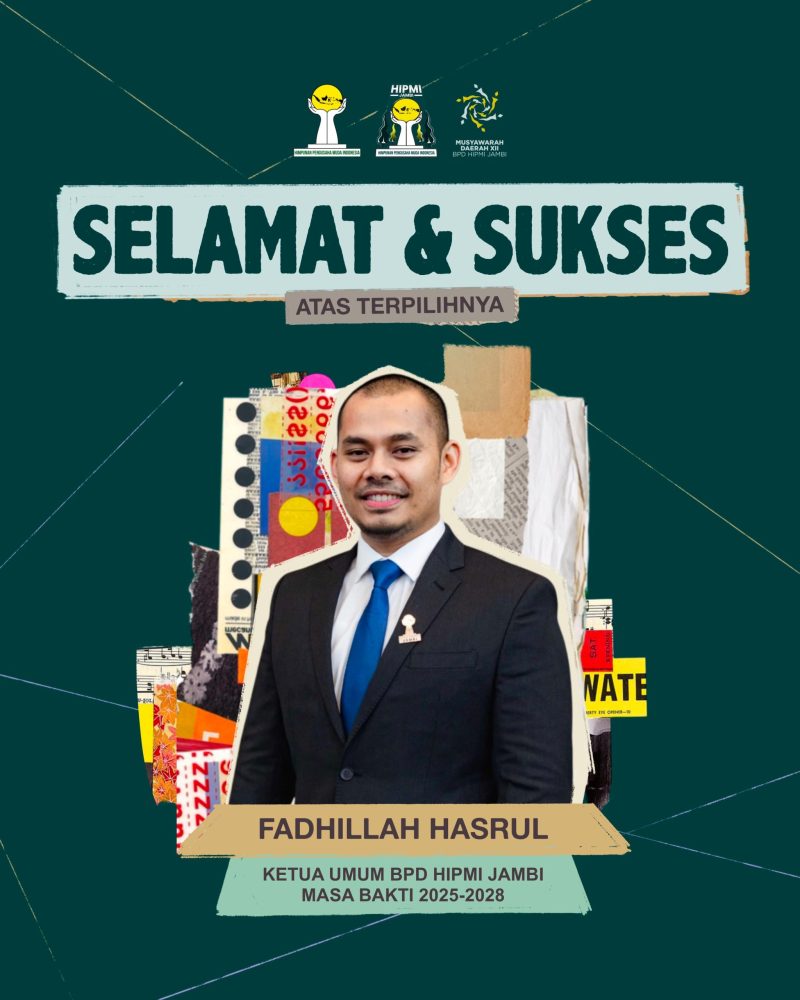
Discussion about this post