STABILITAS kawasan Asia Tenggara kembali terguncang, ketegangan militer yang kembali terjadi “api dalam sekam” di perbatasan Thailand dan Kamboja beberapa hari terakhir menjadi pengingat bahwa konflik perbatasan di kawasan Asia Tenggara belum sepenuhnya usai.
Dentuman senjata dan pengerahan militer di kawasan suci Kuil Preah Vihear bukan hanya mengguncang kedua negara, tetapi juga menguji komitmen ASEAN dalam menjaga perdamaian regional sebagaimana semangat Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN).
Sejarah Sengketa: dari Warisan Kolonial ke Kontestasi Nasionalisme
Akar konflik Thailand-Kamboja dapat ditelusuri sejak era kolonial. Ketika Prancis menjajah Indochina, mereka menyusun peta yang memasukkan Kuil Preah Vihear ke dalam wilayah Kamboja. Setelah kemerdekaan kedua negara, muncul sengketa mengenai batas wilayah, terutama karena kuil tersebut berada di atas tebing yang secara geografis lebih mudah diakses dari Thailand.
Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada dalam wilayah Kamboja, “The Temple of Preah Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia.” (ICJ Judgment, Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), 1962, para. 98). Namun, Thailand menolak sepenuhnya mengakui putusan tersebut, terutama karena tidak mencakup zona penyangga di sekitar kuil.
Lima dekade kemudian, Kamboja kembali mengajukan permohonan interpretasi kepada ICJ. Dalam putusan 11 November 2013, ICJ menegaskan: “Thailand is under an obligation to withdraw from the territory of Cambodia the Thai military or police forces… stationed in the area adjacent to the Temple.”(ICJ Judgment, Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962, para. 107). Namun, bentrokan tetap terjadi, menunjukkan bahwa hukum internasional tanpa kepatuhan adalah norma kosong.
Dalam dinamika geopolitik, wilayah ini memiliki nilai strategis, karena berada di perlintasan penting yang menghubungkan jalur darat dan kontrol atas sumber daya serta simbol kebudayaan nasional.
Jalur Penyelesaian Sengketa: Antara Litigasi, Diplomasi dan Kekuatan Bersenjata
Dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa antarnegara terbagi menjadi dua pendekatan besar:
Pertama, penyelesaian damai (pacific settlement), yang terbagi lagi menjadi dua: Litigasi, yakni membawa kasus ke lembaga yudisial internasional seperti ICJ dan Non-litigasi, seperti perundingan bilateral, mediasi, konsiliasi, maupun melalui peran organisasi internasional.
Kedua, penyelesaian non-damai (coercive means) seperti Retorsi; pengusiran diplomat, Reprisal, Blokade wilayah secara damai, dan Perang atau Penggunaan kekuatan militer.
Dalam Piagam PBB Pasal 33 ayat (1), disebutkan bahwa sengketa antarnegara wajib diselesaikan secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, peradilan, atau sarana damai lainnya. Jalur litigasi seperti ke ICJ hanya efektif jika kedua pihak tunduk dan menghormati putusan, yang dalam kasus ini masih menjadi masalah utama.
Di sisi lain, jalur non-litigasi seperti mediasi, rekonsiliasi, atau negosiasi bilateral menjadi instrumen yang perlu terus dihidupkan. Sayangnya, kepercayaan antara Thailand dan Kamboja kerap naik-turun, sehingga pendekatan diplomatik membutuhkan fasilitator pihak ketiga yang netral dan kredibel.
Dalam konteks ASEAN, Deklarasi ZOPFAN (1971) menjadi pijakan normatif bahwa setiap anggota wajib menahan diri dari penggunaan kekerasan dan memilih jalur damai dalam menyelesaikan sengketa. “The Southeast Asian countries shall make concerted efforts to ensure that their region is free from any form or manner of interference by outside Powers… and settle disputes peacefully.”
Deklarasi ini menjadi fondasi nilai-nilai damai ASEAN. Namun, dalam praktiknya, ZOPFAN sering dianggap hanya sebagai dokumen simbolik tanpa mekanisme implementasi yang kuat. Oleh karena itu, bentrokan senjata di wilayah tersebut sejatinya mencederai komitmen bersama yang telah lama dijalin.
Peran Strategis ASEAN dan Indonesia
ASEAN tidak boleh bersikap pasif. Konflik ini membutuhkan keterlibatan aktif melalui mekanisme High-Level Consultation, atau bahkan emergency summit antar Menteri Luar Negeri atau Kepala Negara. ASEAN memiliki perangkat seperti ASEAN Political-Security Community dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) untuk mendorong penyelesaian damai.
Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan dan pemrakarsa ZOPFAN, perlu mengambil inisiatif. Pendekatan formal melalui mekanisme ASEAN dapat dikombinasikan dengan diplomasi informal (track II diplomacy), misalnya dengan memfasilitasi confidence-building measures antara militer dan pemimpin lokal kedua negara.
Usulan Zona Demiliterisasi dan Pengelolaan Bersama
Salah satu opsi strategis adalah menjadikan kawasan sengketa sebagai zona demiliterisasi (Demilitarized Zone/DMZ) yang tidak diisi pasukan militer dari kedua negara, dan dikelola bersama sebagai situs warisan budaya dunia dan pariwisata lintas batas.
UNESCO, sebagai pihak yang pernah menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai World Heritage Site (2008), dapat dilibatkan untuk menciptakan kerangka pengelolaan multinasional yang damai dan produktif.
Model pengelolaan bersama ini bisa mengadopsi pendekatan serupa seperti yang pernah diterapkan antara Argentina dan Chili dalam sengketa Laguna del Desierto, atau Korea Selatan dan Korea Utara dalam zona DMZ.
Pelajaran Berharga untuk Indonesia
Indonesia harus belajar dari konflik ini. Sengketa perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia (di Kalimantan Utara dan Selat Malaka), Timor Leste (di Oecusse dan Naktuka), hingga Palau dan Vietnam, menunjukkan pentingnya percepatan penyelesaian tapal batas.
Penundaan hanya memperbesar potensi konflik, baik horizontal (masyarakat lokal) maupun vertikal (antarnegara), dan ketidakpastian batas membuka ruang konflik, eksploitasi sumber daya ilegal, serta klaim sepihak.
Penutup
Konflik perbatasan bukan semata soal garis di peta, tetapi soal harga diri, sejarah, dan masa depan kawasan. Sengketa Thailand–Kamboja seharusnya menjadi titik balik peran nyata ASEAN sebagai security community.
Hukum internasional dan instrumen regional sudah tersedia, tinggal keberanian politik untuk menjalankannya. Indonesia sebagai natural leader di ASEAN harus mendorong penyelesaian damai dan menjadi jembatan diplomasi yang aktif.
Sebab perdamaian di kawasan adalah fondasi bagi integrasi ekonomi, stabilitas sosial, dan masa depan generasi ASEAN berikutnya. (***)







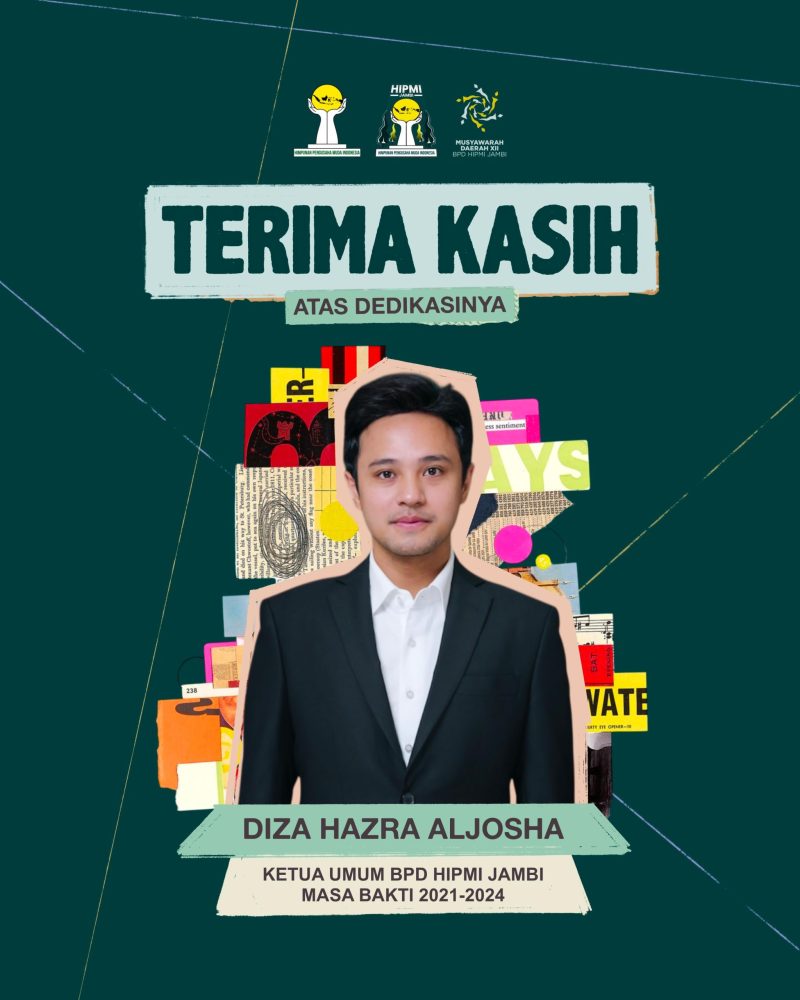
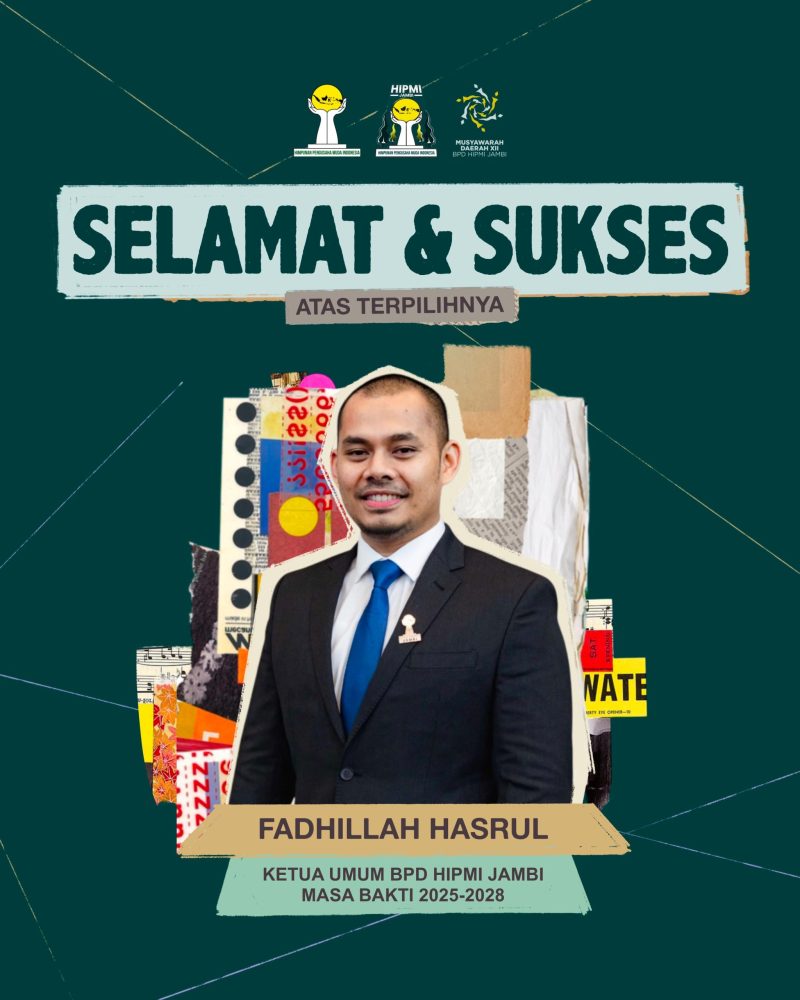
Discussion about this post